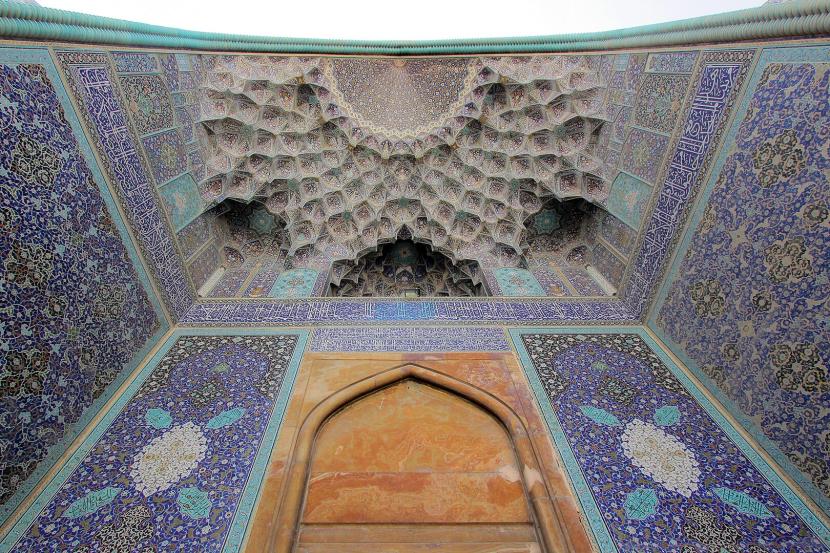Ilustrasi Menulis dengan AI. Sumber: https://www.canva.com/design
Ilustrasi Menulis dengan AI. Sumber: https://www.canva.com/designBaru-baru ini fenomena brain rot semakin digaungkan di tengah makin maraknya penggunaan ChatGPT dan alat bantu generative AI lainnya dalam dunia akademik.
Muncul kegelisahan yang semakin terasa bahwa esai dan karya tulisan ilmiah tidak sepenuhnya dilakukan oleh manusia, melainkan oleh mesin.
Hasilnya sering mengesankan, baik dari kalimat yang terstruktur logis, bahasa yang rapi dan runut, hingga pola penulisan yang baik. Semuanya menjadi serba mudah dan cepat.
Fenomena ini menyita perhatian akademisi karena muncul istilah brainrot akademik atau kemunduran intelektual akibat ketergantungan pada AI.
Jika AI yang menyusun dan menulis, lalu apakah manusia masih terlibat dalam proses berpikirnya?
Paradoks Generative AI: Jalan Pintas dan Pengendali Cara Berpikir
Kemunculan AI dalam dunia akademik memang tidak bisa dilepaskan dari realita sistem pendidikan yang ada. Misalnya, baik mahasiswa maupun dosen dituntut untuk cepat lulus, banyak publikasi tulisan dan jurnal, sementara kegiatan administratif yang dilakukan juga tidak sedikit.
Dalam kondisi ini, penggunaan generative AI menjadi solusi praktis.
Sayangnya, fenomena ini memperkuat sebuah paradoks yang cenderung menuduh bahwa teknologi telah membuat manusia menjadi semakin minim dalam berpikir dan merenung.
Padahal, bisa jadi yang menyebabkan hal tersebut adalah budaya akademik itu sendiri. Hasil akhir lebih dihargai daripada proses, angka lebih dilihat daripada makna, dan performa instan lebih tampak daripada pembelajaran jangka panjang.
Paradoks penggunaan AI ini juga terjadi di tingkat global. Teknologi seperti ChatGPT dan berbagai platform AI lainnya mayoritas dikembangkan oleh negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Eropa, dan sebagian Asia Timur.
 Ilustrasi Artificial Intelligence (AI). Foto: Shutterstock
Ilustrasi Artificial Intelligence (AI). Foto: ShutterstockSementara negara-negara berkembang seperti Indonesia, berada di posisi sebagai pengguna.
Dengan kata lain, teknologinya dipakai, tetapi kita tidak terlibat dalam membentuk cara kerjanya.
Hal ini menimbulkan dilema baru. Di satu sisi, AI membuka akses informasi dan alat bantu belajar yang canggih.
Di sisi lain, AI yang digunakan untuk membantu menulis, berpikir, bahkan belajar, dibentuk dari data, nilai, dan cara pandang yang belum tentu sesuai dengan konteks lokal di negara berkembang.
Maka menjadi suatu pertanyaan bahwa ketika kita menggunakan mesin ini untuk belajar, siapa yang mengendalikan cara kita berpikir? Apa yang dianggap logis, penting, atau mungkin valid dalam sistem itu, belum tentu sesuai dengan pengalaman dan realitas kita di sini.
Hasil Studi MIT: Brain Rot sebagai Cognitive Debt
Sebuah penelitian yang dilakukan MIT Media Lab tahun 2025 memberikan temuan tentang dampak penggunaan AI dalam tulisan.
Dalam studi berjudul Your Brain on ChatGPT, peneliti membagi partisipan ke dalam tiga kelompok.
Pertama, menulis secara manual, kedua menggunakan mesin pencari, dan ketiga menggunakan AI yaitu ChatGPT. Aktivitas otak partisipan dipantau menggunakan Electroencephalogram (EEG) selama kegiatan menulis.
Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kelompok yang menggunakan AI mengalami penurunan aktivitas otak paling drastis dibanding yang menulis tanpa alat bantu.
Selain itu, kelompok ketiga ini juga tidak mampu mengingat isi tulisan mereka beberapa menit setelah selesai. Namun, karya tulis yang dihasilkan rapi secara teknis.
Peneliti MIT menyebut fenomena ini sebagai cognitive debt, yaitu utang berpikir akibat tidak melibatkan otak secara aktif dalam proses intelektual, sama dengan yang kita kenal dengan istilah brain rot.
Penelitian ini menggambarkan bahwa meskipun AI dapat memproduksi teks yang sangat baik, namun keterlibatan manusia terhadap pemaknaan dan pemberian argumen di balik tulisan justru semakin tidak jelas.
UNESCO: Penggunaan AI Harus Etis dan Dipertanggungjawabkan
Dalam Guidance for Generative AI in Education and Research (2023), UNESCO mengambil pendekatan bahwa kehadiran AI tidak untuk ditolak, tapi mendorong penggunaannya lebih bertanggung jawab.
Melalui dokumen ini, UNESCO menekankan bahwa generative AI seperti ChatGPT hanya boleh digunakan jika ada transparansi, etika, dan pemahaman kritis terhadap teknologinya.
Terdapat tiga hal utama yang perlu digaris bawahi.
Pertama, disclosure, di mana setiap penggunaan AI dalam proses penulisan harus disampaikan secara jujur.
Kedua, pentingnya literasi AI, supaya bukan sekadar tahu cara menggunakan, tetapi memahami bagaimana AI bekerja, apa batasnya, dan potensi bias yang mungkin muncul.
Ketiga, AI tidak untuk menggantikan proses belajar. AI dihadirkan sebagai alat bantu untuk memperkuat pemahaman dan kreativitas, bukan untuk menggantikan.
UNESCO menyadari bahwa AI dapat menjadi alat bantu yang bermanfaat, jika dilakukan dengan pendampingan dan kebijakan yang tepat supaya tidak memundurkan kemampuan berpikir kritis.
Pentingnya Literasi AI dan Mendorong Reformasi Budaya Akademik
Menghadapi situasi tersebut di atas, maka pendekatan yang sifatnya melarang penggunaan AI saja tidak akan cukup. Sebuah perubahan secara menyeluruh diperlukan, mulai dari cara memahami teknologi hingga sistem penilaian dalam bidang akademik.
Literasi AI harus menjadi bagian dari pendidikan, tidak hanya sebagai materi teknis, tetapi juga sebagai materi terkait etis dan refleksi sebagaimana disampaikan oleh UNESCO.
AI tetap bisa digunakan, namun bukan sebagai titik awal menulis. AI dapat dijadikan alat bantu untuk melakukan koreksi dan revisi misalnya.
Studi MIT menunjukkan bahwa partisipan yang menulis manual terlebih dulu, kemudian menggunakan AI untuk menyusun ulang, tetap menunjukkan aktivitas kognitif yang tinggi.
Artinya, AI dapat menjadi alat bantu yang positif, selama tidak dijadikan satu-satunya pengganti proses berpikir sejak awal.
Sementara itu, institusi pendidikan juga dapat melakukan reformasi terhadap sistem evaluasinya.
Penilaian tidak hanya terfokus pada hasil atau output tulisan yang dikumpulkan, tetapi juga pada proses penulisan. Bagaimana ide muncul, bagaimana argumen dikembangkan, dan sejauh mana penulis terlibat dalam merefleksikan pemikirannya sendiri.
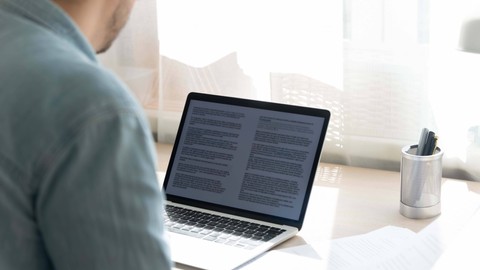 Ilustrasi menulis esai beasiswa. Foto: fizkes/Shutterstock
Ilustrasi menulis esai beasiswa. Foto: fizkes/ShutterstockMenulis adalah Berpikir
Poin refleksi yang dapat kita ambil adalah menulis bukan sekadar merangkai kalimat. Menulis adalah aktivitas berpikir, memahami, dan bertanggung jawab atas apa yang disampaikan dalam tulisan.
Di sisi lain, kehadiran AI dalam dunia akademik tidak bisa dihindari.
Teknologi seperti ChatGPT memang menawarkan efisiensi yang menjadi kebutuhan dalam tuntutan lingkungan yang serba cepat saat ini.
Namun, jika efisiensi itu membuat manusia kehilangan kemampuannya untuk terhubung dengan pikirannya sendiri, maka yang dipertanyakan bukan hanya kualitas tulisan, tetapi masa depan pendidikan itu sendiri.
AI bisa menyusun kata-kata, tetapi hanya manusia yang bisa memberikan makna. Karena pada akhirnya, teknologi hanyalah alat. Manusia tetap menjadi penentu arah.
AI bisa sangat cerdas, tetapi ia tidak tumbuh dari kecemasan, keraguan, kegelisahan, ataupun realitas emosional di tempat kita tinggal.
Maka bukan hanya soal efisiensi atau produktivitas, tetapi apakah kita masih terlibat dalam proses berpikir tersebut?

 1 week ago
8
1 week ago
8